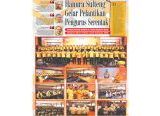Oleh: Zainudin Kismit, Wakil Ketua Hikmah & Kebijakan Publik (HKP) Pemuda Muhammadiyah Kalbar, Ketua Pokja Rumah Demokrasi Kalbar
WACANA pengembalian pemilihan kepala daerah (Pilkada) oleh DPRD kembali mengemuka. Alasan yang kerap dikemukakan terdengar rasional: efisiensi anggaran, pengurangan konflik politik, serta penyederhanaan prosedur demokrasi.
Namun di balik argumen teknokratis tersebut, ada satu pertanyaan mendasar yang tak boleh diabaikan: di mana posisi rakyat dalam demokrasi lokal jika kepala daerah tidak lagi dipilih langsung?
Pertanyaan ini penting, sebab Pilkada bukan sekadar mekanisme administratif, melainkan simbol kedaulatan rakyat di tingkat lokal.
Sejak diberlakukan pascareformasi, Pilkada langsung menjadi ruang partisipasi warga untuk menentukan arah pembangunan daerahnya sendiri.
Ketika hak memilih itu dipindahkan dari prinsip one man, one vote ke ruang rapat parlemen daerah, demokrasi berisiko kehilangan makna partisipatifnya dan menyempit menjadi prosedur elite.
Dalam teori politik, demokrasi tidak pernah dimaknai semata sebagai sistem yang murah atau cepat. Robert A. Dahl menegaskan bahwa demokrasi mensyaratkan partisipasi efektif dan kontrol rakyat atas keputusan politik.
Pilkada langsung memberi ruang bagi rakyat untuk memberi mandat sekaligus sanksi kepada pemimpinnya. Tanpa mekanisme ini, akuntabilitas kekuasaan menjadi kabur.
Carole Pateman, melalui teori demokrasi partisipatoris, juga menekankan bahwa partisipasi bukan hanya soal memilih pemimpin, tetapi sarana pendidikan politik warga.
Dalam konteks ini, Pilkada langsung berfungsi membangun kesadaran politik, rasa memiliki terhadap pemerintahan, serta legitimasi pemimpin di mata publik.
Argumen efisiensi anggaran pun perlu dibaca secara jernih. Memang, sejak Pilkada serentak 2015 hingga 2024, biaya penyelenggaraan bervariasi dari puluhan hingga ratusan miliar rupiah per daerah.
Kementerian Keuangan mencatat total anggaran Pilkada 2024 mencapai Rp37,43 triliun untuk 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Namun angka tersebut sejatinya adalah biaya demokrasi, bukan pemborosan, selama ia menjamin hak politik warga negara.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyebut Pilkada langsung maupun tidak langsung bukan hal baru karena pernah diterapkan di Indonesia.
Pernyataan itu benar. Namun sejarah juga mencatat bahwa sistem Pilkada oleh DPRD menyisakan persoalan serius: politik transaksional, dominasi elite, serta lemahnya legitimasi kepala daerah.
Pilkada langsung hadir sebagai koreksi atas praktik tersebut. Dalam perspektif demokrasi partisipatoris, partisipasi warga merupakan proses pembelajaran kolektif.
Melalui pemilihan langsung, warga belajar menilai program, integritas, dan kepemimpinan. Ketika ruang ini dihapus, demokrasi kehilangan fungsi edukatifnya dan rakyat kembali diposisikan sebagai objek kebijakan, bukan subjek politik.
Representasi yang Tidak Selalu Representatif
Secara teoritik, DPRD memang representasi rakyat. Namun Hanna Pitkin mengingatkan bahwa representasi tidak cukup dimaknai sebagai mandat formal, melainkan harus diwujudkan melalui tindakan substantif sesuai kepentingan publik.
Dalam praktik politik Indonesia, DPRD kerap terjebak dalam disiplin partai, kalkulasi koalisi, dan kepentingan elite nasional.
Dalam kondisi tersebut, Pilkada oleh DPRD berisiko menjadi transaksi politik tertutup. Prosesnya sulit diawasi publik, minim transparansi, dan rentan kompromi kepentingan. Rakyat tidak memiliki mekanisme langsung untuk mengoreksi keputusan itu, selain menunggu pemilu berikutnya.
Lebih jauh, kepala daerah yang lahir dari proses elite cenderung memiliki loyalitas ganda: kepada rakyat dan kepada kekuatan politik yang memilihnya.
Dalam praktik, loyalitas kepada elite sering kali lebih dominan, sehingga kebijakan publik menjadi elitis, bukan populis.
Banyak negara mengalami democratic backsliding—kemunduran demokrasi yang berlangsung perlahan dan legal.
Salah satu tandanya adalah pengurangan ruang partisipasi warga atas nama stabilitas dan efisiensi. Mengembalikan Pilkada ke DPRD berpotensi menjadi bagian dari tren tersebut.
Dalam jangka panjang, partisipasi politik masyarakat menurun, kepercayaan publik terhadap institusi politik melemah, dan apatisme tumbuh. Demokrasi lokal pun berisiko berubah menjadi prosedur formal tanpa keterlibatan substantif warga.
Memperbaiki Demokrasi, Bukan Menguranginya
Masalah Pilkada langsung memang nyata: politik uang, polarisasi, dan biaya tinggi. Namun solusi atas problem demokrasi tidak boleh berupa pengurangan demokrasi itu sendiri.
Dalam perspektif demokrasi deliberatif Jürgen Habermas, kualitas demokrasi ditentukan oleh keterbukaan ruang publik, transparansi, dan diskursus rasional.
Karena itu, negara seharusnya fokus pada empat agenda utama. Pertama, pengetatan pengawasan dana kampanye yang selama ini masih bersifat administratif dan belum menyentuh praktik riil di lapangan.
Kedua, penegakan hukum tegas terhadap politik uang agar memberi efek jera, bukan sekadar simbol penindakan.
Ketiga, transparansi pencalonan dan penguatan partai politik melalui kaderisasi yang terbuka dan berbasis kapasitas, bukan sekadar modal dan popularitas.
Keempat, pendidikan politik masyarakat yang berkelanjutan agar pemilih tidak mudah dimanipulasi oleh uang, hoaks, dan politik identitas.
Saat ini, lima dari delapan partai politik di parlemen menyatakan setuju Pilkada dikembalikan ke DPRD.
Jika DPRD tetap ingin diberi peran lebih besar, maka harus ada mekanisme uji publik terbuka, keterlibatan masyarakat sipil, serta proses pemilihan yang transparan dan disiarkan ke publik. Tanpa itu, pemilihan oleh DPRD hanyalah kemunduran yang dilembagakan.
Pada akhirnya, pertanyaan tentang siapa yang memilih kepala daerah adalah pertanyaan tentang siapa pemilik demokrasi.
Apakah demokrasi milik rakyat, atau sekadar mekanisme bagi elite untuk mengatur kekuasaan dengan lebih nyaman?
Jika hak memilih pemimpin daerah dicabut dari rakyat, demokrasi kehilangan roh utamanya: kedaulatan warga negara. Demokrasi mungkin tidak mati seketika, tetapi ia bisa layu perlahan hingga akhirnya kehilangan makna. (*)