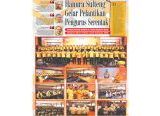Oleh : Agus Fitriangga, MKM., Dosen Departemen Kedokteran Komunitas, Fakultas Kedokteran, Universitas Tanjungpura
SETIAP tahun, 1 Desember datang dan pergi. Spanduk Hari HIV/AIDS dunia dipasang, acara seremonial digelar, lalu pelan-pelan menguap dari ingatan. Yang tertinggal justru sesuatu yang tidak pernah ikut menghilang: stigma.
Kita sibuk bicara “zero discrimination” di podium, tapi di ruang keluarga, tempat kerja, bahkan fasilitas kesehatan, orang dengan HIV/AIDS (ODHA) masih sering “digosting” – dihindari, diabaikan, diperlakukan seolah tidak ada.
Padahal, secara angka, HIV bukan lagi isu jauh di Afrika atau kota besar lain. Di Kalimantan Barat, Dinas Kesehatan provinsi mencatat total 1.488 kasus HIV/AIDS hingga akhir 2023. Angka ini bukan angka kecil untuk provinsi yang penduduknya sekitar lima jutaan.
Di level global, 40,8 juta orang hidup dengan HIV pada 2024, dengan 1,3 juta infeksi baru dan 630 ribu kematian terkait AIDS hanya dalam satu tahun.(UNAIDS, 2024). Jadi, kalau kita merasa masalah ini “sudah lewat”, kita sedang menipu diri sendiri.
Di level nasional, situasinya juga belum nyaman. Estimasi terbaru menunjukkan sekitar 570.000 orang hidup dengan HIV di Indonesia, namun baru sekitar 31% yang mengakses pengobatan antiretroviral dan hanya 14% yang mencapai supresi virus (UNAIDS, 2024).
Artinya, sebagian besar belum terhubung dengan layanan pengobatan yang memadai. Mari turun lebih lokal. Di Kota Pontianak, Kepala Dinas Kesehatan menyebutkan bahwa warga Pontianak yang terpapar HIV tahun 2023 ada 95 orang, dan tahun 2024 tercatat 92 orang (profil Dinkes Pontianak, 2024) turun tipis, tapi tetap puluhan kasus baru tiap tahun.
Di Kabupaten Ketapang, sampai November 2024, tercatat 113 penderita HIV/AIDS, naik dari 103 kasus pada 2023 (Suara Kalbar, 2025). Artinya, di sejumlah kabupaten kasus justru naik.
Jadi, HIV bukan cerita “dulu” – ini realitas hari ini, di Kalbar, di sekitar kita. Salah satu penghalang terbesar bukan teknologi medis, tapi faktor sosial: stigma, diskriminasi, dan ketidaktahuan.
Penelitian dan review ilmiah beberapa tahun terakhir konsisten menunjukkan hal yang sama: stigma terhadap ODHA terjadi hampir di semua level – keluarga, teman, sekolah, tempat kerja, bahkan media.
Sebuah review tahun 2023 menunjukkan bahwa stigma menjadi salah satu hambatan paling besar dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia (Maulidiah, 2023).
Ini bukan isu moral, ini isu kesehatan publik. Stigma membuat orang takut tes, takut berobat, dan akhirnya terlambat tertangani.
Studi di berbagai daerah di Indonesia juga menemukan bahwa rendahnya pengetahuan tentang HIV berhubungan dengan tingginya stigma, terutama di kalangan remaja dan pelajar (Oliviawati, 2024).
Ada yang masih percaya HIV menular lewat berjabat tangan, berbagi piring, atau duduk berdekatan. Akibatnya, ODHA diasingkan, disindir, atau dijauhi.
Di kampus ternama seperti Universitas Indonesia, riset terbaru bahkan menunjukkan stigma di kalangan mahasiswa masih terbagi antara tinggi dan rendah – artinya, bahkan kelompok terdidik pun belum kebal dari prasangka (Widyaningtyas, 2022).
Stigma ini bukan cuma berupa kata-kata kasar. Bentuk halusnya jauh lebih berbahaya: diam, menjauh, tidak mau menyapa, memindahkan kursi, atau sekadar menghindari topik.
Ini yang saya sebut “ghosting” ODHA. Mereka hadir secara fisik, tapi diperlakukan seolah tidak ada.
Di lingkungan kerja, ada ODHA yang sengaja tidak diundang rapat, tidak diberi tugas penting, atau pelan-pelan “disingkirkan”. Di fasilitas kesehatan, ada yang ditunda pelayanannya, dilabeli, atau dibicarakan di belakang.
Yang lebih mengkhawatirkan, stigma ini kadang justru dilegitimasi oleh kebijakan. Laporan masyarakat sipil tahun 2024 menyoroti maraknya peraturan daerah yang diskriminatif dengan dalih mencegah penyebaran HIV/AIDS.
Akibatnya, kelompok rentan – termasuk minoritas seksual dan perempuan dengan HIV – justru semakin takut mengakses layanan kesehatan karena khawatir teridentifikasi, disorot, atau bahkan dijerat aturan (infid, 2024). Alih-alih menurunkan penularan, regulasi seperti ini membuat epidemi bergeser ke “bawah tanah”.
Di Kalimantan Barat, kita sering bangga dengan nilai kekeluargaan dan gotong royong. Tapi kehangatan itu sering berhenti di pintu rumah ketika topiknya HIV.
Ada anak muda yang positif HIV, lalu dipaksa pindah kamar, piring dan gelasnya dipisahkan, seolah HIV bisa menular lewat sendok. Ada ibu rumah tangga yang tertular dari suami, tapi justru dialah yang disalahkan, distempel “nakal”, sementara suami dan jaringannya dibiarkan hilang dari diskusi. Stigma tidak hanya kejam, tapi juga salah sasaran.
Padahal, ilmu pengetahuan sudah jelas. HIV menular melalui hubungan seksual tanpa kondom, penggunaan jarum suntik tidak steril, transfusi darah yang tidak aman, dan dari ibu ke bayi bila tidak mendapat intervensi.
Tidak menular lewat pelukan, cium pipi, batuk, bersin, atau berbagi piring. Namun gap antara sains dan persepsi masyarakat masih lebar. Tanpa literasi kesehatan yang kuat, mitos akan selalu menang melawan fakta.
Di sisi lain, kita juga harus jujur bahwa layanan kita belum sepenuhnya ramah. Masih ada tenaga kesehatan yang memandang ODHA dengan curiga, mengomentari gaya hidup, atau mengaitkan HIV semata dengan “dosa”.
Padahal, penelitian menunjukkan bahwa sikap tenaga kesehatan berpengaruh langsung pada mau atau tidaknya pasien melanjutkan pengobatan. Ketika ruang layanan saja tidak aman, jangan heran kalau orang memilih untuk diam dan menghilang dari sistem.
Bagi anak muda di Pontianak dan kabupaten lainnya, HIV sering dianggap “jauh” dan hanya terjadi pada kelompok tertentu. Padahal, data menunjukkan pengidap HIV didominasi laki-laki usia produktif.
Ini usia mahasiswa, pekerja muda, sopir, barista, content creator, dan profesi lain yang kita temui sehari-hari. Kalau kita terus memelihara stereotip bahwa HIV hanya persoalan “kelompok tertentu”, kita akan terus gagal mendeteksi kasus pada mereka yang merasa dirinya “bukan kelompok risiko”.
Ghosting terhadap ODHA juga terjadi di level kebijakan. HIV sering tidak muncul di headline APBD, tidak jadi prioritas ketika anggaran kesehatan dipotong, kalah oleh isu yang lebih “menjual”.
Padahal, investasi pada tes, pengobatan, konseling, dan kampanye anti-stigma jauh lebih murah dibanding biaya jangka panjang ketika infeksi terus meluas dan produktivitas generasi muda turun.
Bagi provinsi perbatasan seperti Kalbar, yang sedang mengejar ketertinggalan pembangunan, membiarkan HIV “merayap diam-diam” adalah blunder strategis.
Lalu apa yang bisa kita lakukan secara realistis, di luar jargon? Pertama, hentikan ghosting. Kalau di keluarga atau lingkungan kerja kita tahu ada ODHA, perlakukan dia sebagai manusia utuh, bukan virus berjalan.
Dengarkan, jangan menghakimi. Kedua, dorong fasilitas kesehatan, kampus, dan sekolah di Kalbar memperkuat edukasi berbasis bukti, bukan sekadar ceramah moral. Materi khusus tentang HIV, cara penularan, dan hak ODHA perlu masuk ke kelas, Puskesmas, dan ruang publik.
Ketiga, pemerintah daerah – provinsi maupun kabupaten/kota – perlu berani meninjau ulang kebijakan dan Perda yang berpotensi diskriminatif. Pendekatan berbasis hak asasi manusia dan kesehatan publik harus dikedepankan, bukan pendekatan yang hanya mengatur dan menghukum.
Keempat, kita perlu memastikan program penanggulangan HIV benar-benar menjangkau kelompok kunci, termasuk mereka yang sering diserang stigma ganda: karena identitas, karena profesi, dan karena status HIV-nya.
Pada akhirnya, HIV adalah cermin kejujuran kita sebagai masyarakat. Teknologi obat makin maju, data makin lengkap, panduan nasional makin jelas, tapi kalau stigma tetap dipelihara, kita hanya memindahkan masalah dari ruang konferensi ke lorong sunyi kehidupan sehari-hari.
ODHA tidak butuh dikasihani, mereka butuh diakui, dilindungi, dan diperlakukan layak – di rumah, di sekolah, di tempat kerja, dan di fasilitas kesehatan.
Menjelang 1 Desember ini, mungkin kita tidak perlu menambah banyak slogan baru. Cukup satu komitmen sederhana: berhenti ghosting ODHA. Ajak bicara, duduk bersama, buka ruang kerja dan pelayanan yang aman, koreksi bercanda yang melukai, dan beranikan diri melawan kebijakan yang diskriminatif.
Kalau stigma “tak pernah kedaluwarsa”, biarkan justru empati, ilmu pengetahuan, dan keberanian kita yang menggantikan masa berlakunya. Karena di tengah semua angka dan grafik, yang kita pertaruhkan bukan sekadar statistik – tapi martabat manusia. (*)